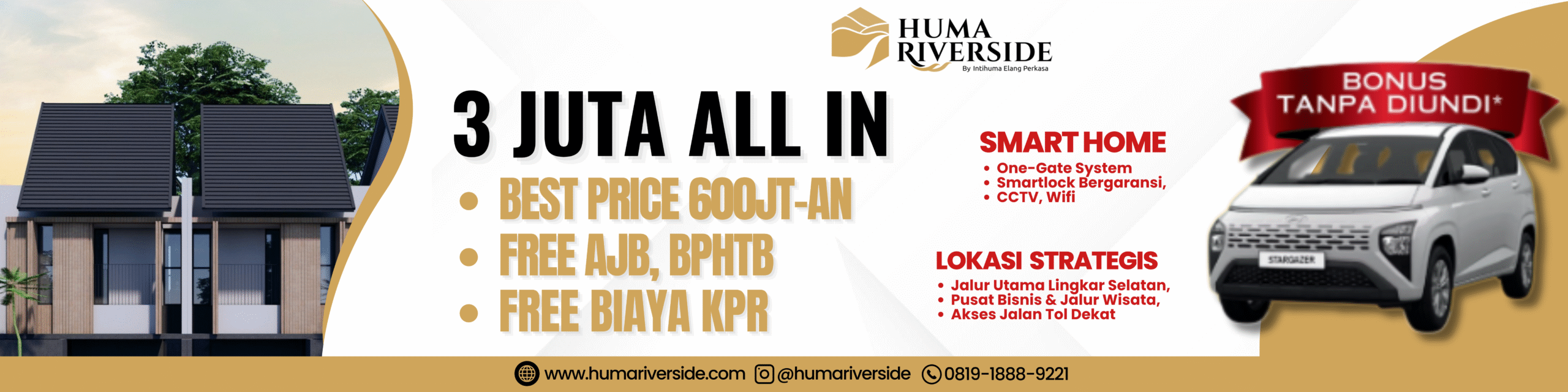Ketegangan Guru dan Murid Ungkap Problem Pendidikan Modern
adainfo.id – Mencuatnya kasus konflik antara seorang guru dan murid pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia memantik keprihatinan luas dari berbagai kalangan.
Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi sorotan publik karena aspek kekerasan yang menyertainya, tetapi juga membuka diskursus lebih dalam mengenai kondisi relasi pendidikan di Indonesia.
Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang peserta didik justru dipersepsikan sebagai arena konflik yang sarat ketegangan antara pendidik dan murid.
Fenomena ini menjadi ironi di tengah upaya pemerintah yang tengah menggencarkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan iklim pendidikan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi.
Namun, kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan struktural yang tidak sederhana.
Sekolah sebagai Ruang Sosial yang Semestinya Demokratis
Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta atau yang akrab disapa Abe, menilai konflik yang terjadi tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai persoalan individual antara guru dan murid.
Menurutnya, sekolah merupakan ruang sosial yang seharusnya memungkinkan terjadinya dialog demokratis antara berbagai aktor pendidikan.
Ia menegaskan bahwa proses pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan konsep tri pusat pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Ketika ketiganya tidak terintegrasi dengan baik, relasi pedagogis menjadi rapuh dan rentan konflik.
“Jadi, konflik ini bukan semata konflik guru dan murid saja. Ada peta besar sebab akar persoalan ini, hubungan guru, murid, dan wali menjadi transaksional,” paparnya dikutip Senin (09/02/2026).
Menurut Abe, keterpisahan antara ketiga unsur tersebut membuat pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses sosial yang membentuk karakter dan nilai.
Sekolah tidak lagi menjadi ruang bersama untuk tumbuh, melainkan arena formal yang kaku dan penuh tekanan.
Dampak Panjang Liberalisasi Pendidikan
Abe menilai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini merupakan bagian dari cerita panjang dampak liberalisasi pendidikan yang telah berlangsung sejak dekade 1980-an.
Proses tersebut, menurutnya, secara perlahan menggeser filosofi dasar pendidikan dari proses pemanusiaan menjadi mekanisme pasar.
Ia menyebut fenomena ini sebagai neoliberalisme pendidikan, di mana sekolah diposisikan layaknya entitas ekonomi yang menjual jasa pendidikan.
Relasi antara wali murid, sekolah, dan guru pun cenderung bersifat transaksional, bukan lagi relasi nilai.
Prosedur transaksi ini, lanjut Abe, terlihat dari tingginya biaya pendidikan yang dibayarkan wali murid dengan harapan anak mendapatkan layanan pendidikan terbaik.
Dalam posisi ini, wali murid merasa memiliki hak komplain yang kuat, sementara guru kehilangan posisi sebagai pamong moral.
“Melainkan guru sebagai sektor yang diawasi secara legalistik bahkan dapat berujung ke proses hukum,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai menempatkan guru dalam situasi dilematis.
Di satu sisi, mereka dituntut menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan karakter, namun di sisi lain dibayangi risiko hukum ketika melakukan tindakan disiplin terhadap murid.
Sekolah Kehilangan Watak Paguyuban
Abe menyayangkan perubahan watak sekolah yang semakin menjauh dari konsep paguyuban pendidikan.
Sekolah, menurutnya, kini lebih menyerupai arena relasi ekonomi yang diwarnai kepentingan dan kontrak tidak tertulis antara penyedia dan pengguna jasa pendidikan.
Dalam situasi tersebut, baik guru maupun murid menjadi aktor yang sama-sama terjebak dalam sistem besar yang membentuk perilaku dan relasi mereka.
Konflik yang muncul dipandang sebagai gejala dari kerusakan sistemik, bukan semata kesalahan individu.
Keadaan ini membuat upaya perbaikan menjadi sangat kompleks. Peningkatan kapasitas guru dinilai penting, namun tidak akan cukup jika tidak disertai perombakan sistem pendidikan secara menyeluruh.
“Jalan bahwa guru harus ada peningkatan kapasitas jelas itu, tetapi kan tidak cukup karena sistemnya sudah carut-marut begini,” jelasnya.
Ketakutan Guru dan Pudarnya Ruang Dialog
Dari perspektif sosiologi, Abe menilai semua pihak dalam ekosistem pendidikan memiliki potensi berada di posisi benar maupun salah.
Namun, sistem yang berlaku saat ini justru menciptakan iklim ketakutan yang menghambat proses dialog dan pembelajaran.
Ia mengilustrasikan kondisi di mana guru merasa takut menegur murid karena khawatir dilaporkan dan berujung pada proses hukum.
Akibatnya, sekolah kehilangan fungsinya sebagai ruang pembentukan warga yang kritis dan demokratis.
“Sekolah bukan lagi ruang dialog kritis, melainkan menjadi ruang yang tunduk pada logika ketakutan dan kontrol pengawasan hukum seperti itu,” bebernya
.
Dalam situasi tersebut, relasi pendidikan menjadi kering dan prosedural.
Interaksi antara guru dan murid lebih didorong oleh kepatuhan administratif dibandingkan kepercayaan dan tanggung jawab moral.
Tantangan Implementasi Sekolah Aman dan Nyaman
Kasus ini juga menyoroti tantangan besar dalam implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
Regulasi ini menuntut perubahan budaya, bukan sekadar kepatuhan administratif.
Budaya aman dan nyaman tidak hanya soal ketiadaan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup rasa aman secara psikologis bagi seluruh warga sekolah.
Dalam konteks ini, guru membutuhkan perlindungan dan kejelasan peran, sementara murid memerlukan ruang aman untuk berekspresi dan belajar.
Namun, selama relasi pendidikan masih dibingkai dalam logika transaksional dan legalistik, tujuan tersebut sulit tercapai.
Kebijakan berpotensi berhenti sebagai dokumen normatif tanpa perubahan nyata di tingkat praktik.
Abe menekankan perlunya perombakan mendasar terhadap seluruh ekosistem pendidikan yang terjebak dalam neoliberalisme.
Menurutnya, relasi transaksional yang lahir dari liberalisasi pendidikan berpotensi membahayakan semua pihak karena menciptakan ekosistem yang tidak kondusif bagi lahirnya praktik-praktik kebaikan.
Ia menilai sistem semacam ini hanya akan melanggengkan konflik yang terus berulang dan semakin meluas seiring viralitas kasus di ruang publik.
Pola tersebut, menurutnya, harus diputus jika Indonesia ingin membangun pendidikan yang berkeadaban.
“Berani tidak bangsa ini, negara ini, melakukan perombakan sistem secara radikal dan mengembalikannya pada Undang-Undang Dasar kita,” tutupnya.
Kasus pertikaian guru dan murid ini pun menjadi cermin dari persoalan struktural pendidikan nasional.
Di tengah komitmen pemerintah untuk membangun sekolah aman dan nyaman, tantangan besar masih menghadang pada level relasi, budaya, dan sistem yang membentuk praktik pendidikan sehari-hari.