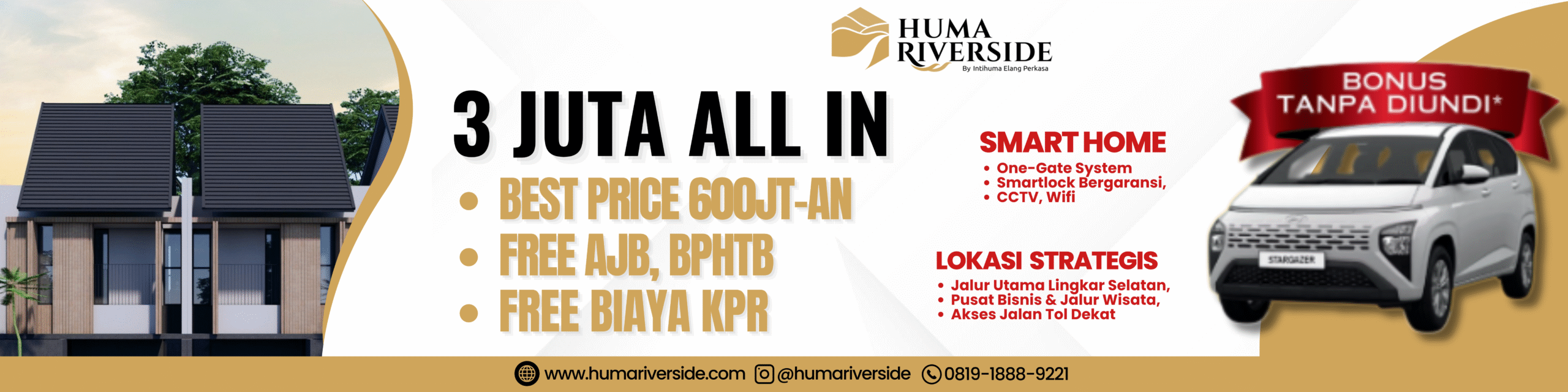Tari Tradisional Tak Boleh Tinggal Nama: Revitalisasi Budaya Lewat Lensa Generasi Muda
Di era globalisasi dan dominasi budaya populer, generasi muda Indonesia mengalami pergeseran preferensi dalam mengekspresikan identitas dan gaya hidup. Salah satu bentuk nyata dari pergeseran ini adalah meningkatnya popularitas budaya Korea Selatan, khususnya K-Pop, di kalangan remaja dan anak muda.
Hal ini tidak hanya tercermin dari konsumsi musik dan fashion, tetapi juga dalam antusiasme terhadap koreografi dance yang dipopulerkan oleh grup-grup K-Pop.
Platform digital seperti TikTok dan Instagram menjadi wadah utama bagi generasi muda untuk menampilkan keterampilan menari mereka, yang sebagian besar merujuk pada koreografi artis luar negeri ketimbang tari-tari tradisional lokal.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terkait pelestarian budaya Nusantara, khususnya seni tari tradisional. Tari tradisional yang sarat akan nilai-nilai filosofis, spiritual, serta refleksi atas kearifan lokal, kini mulai kehilangan daya tariknya di mata generasi muda.
Dalam beberapa kasus, kesenian lokal hanya dikenal sebatas mata pelajaran sekolah tanpa keterlibatan emosional yang mendalam. Padahal, seperti dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2009), kebudayaan adalah identitas sekaligus kekuatan sosial suatu bangsa yang tidak dapat dilepaskan dari kesadaran kolektif masyarakatnya.
Data yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2023 memperkuat kekhawatiran ini. Tercatat bahwa minat generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional, termasuk tari daerah, mengalami penurunan sebesar hampir 35% dalam lima tahun terakhir.
Penurunan ini bukan hanya berdampak pada kelangsungan seni tradisi, tetapi juga mengancam transfer pengetahuan antar generasi. Seni tari yang pada masa lalu diwariskan secara lisan dan praktik langsung dari guru ke murid kini mulai terputus akibat minimnya partisipasi generasi baru.
Kondisi ini diperparah oleh kurangnya inovasi dalam penyajian dan promosi tari tradisional di media digital. Sementara budaya populer seperti K-Pop didukung oleh strategi promosi global yang masif dan adaptif terhadap tren teknologi, seni tradisional Indonesia masih banyak dipromosikan secara konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan kekuatan media sosial.
Hal ini sesuai dengan analisis UNESCO (2017) yang menyatakan bahwa pelestarian budaya lokal di era digital membutuhkan pendekatan kreatif yang menggabungkan teknologi, partisipasi publik, dan kebijakan kultural yang progresif.
Namun demikian, bukan berarti tari tradisional tidak memiliki peluang untuk tetap eksis. Beberapa komunitas seni, lembaga pendidikan, hingga pegiat budaya telah mulai berinovasi dengan mengadaptasi tari daerah ke dalam format digital, termasuk membuat dance challenge versi tari tradisional dan mengunggahnya ke TikTok serta YouTube.
Upaya ini sejalan dengan konsep cultural hybridization (García Canclini, 1995), di mana budaya lokal dapat bertahan dengan beradaptasi dan menyerap elemen-elemen baru tanpa kehilangan esensinya.
Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan influencer muda dalam menghidupkan kembali minat generasi muda terhadap kesenian tradisional. Program seperti muatan lokal, festival digital tari daerah, atau kolaborasi antara seniman tradisional dan kreator konten dapat menjadi jembatan antara warisan budaya masa lalu dan kehidupan generasi masa kini.
Pelestarian tari tradisional bukan semata soal mempertahankan bentuk, tetapi juga menanamkan nilai, makna, dan rasa bangga terhadap identitas budaya bangsa.
Namun harapan belum sirna. Di sejumlah daerah, muncul gerakan-gerakan komunitas kreatif yang mencoba menjembatani tradisi dan zaman. Salah satunya adalah Lens Production Tari, komunitas yang secara konsisten menghadirkan pertunjukan tari tradisional dengan pendekatan kreatif dan segar.
Melalui pelatihan tari untuk berbagai usia dan penampilan publik yang dikemas secara visual menarik, mereka berhasil mengangkat kembali pesona tari-tari nusantara ke tengah perhatian publik, khususnya anak muda.
Penampilan mereka dengan busana adat Batak, Minang, dan Dayak, yang terlihat dalam dokumentasi foto, tidak hanya menunjukkan keberagaman, tetapi juga rasa bangga terhadap budaya sendiri.
Upaya seperti ini sejalan dengan pendekatan revitalisasi budaya yang dikembangkan oleh UNESCO, di mana pelestarian tidak hanya dilakukan lewat dokumentasi, tapi juga dengan menjadikan warisan budaya itu “hidup” kembali dalam praktik keseharian.
Pendekatan ini memerlukan kreativitas, adaptasi, dan kolaborasi antargenerasi. Lens Production memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan dokumentasi kegiatan mereka, menjadikan tari tradisional bukan lagi sesuatu yang eksklusif atau kuno, tapi justru trendi dan relevan.
Tentu saja, gerakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta media massa sangat dibutuhkan. Sekolah-sekolah bisa memasukkan tari tradisional dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik, bukan sekadar formalitas. Media dapat memberikan ruang lebih besar untuk karya budaya lokal, bukan hanya berita viral yang sesaat.
Bahkan kolaborasi dengan content creator atau influencer lokal bisa memperluas jangkauan, sebagaimana pernah dilakukan program Indonesia Menari yang diselenggarakan oleh Galeri Indonesia Kaya.
Revitalisasi budaya bukan berarti memusuhi budaya asing. Justru, saat budaya luar bisa begitu mendunia karena didukung oleh masyarakat dan negara asalnya, kita pun harus mampu membangun dukungan serupa untuk budaya sendiri. Indonesia memiliki ribuan tarian tradisional yang kaya nilai filosofis, estetika, dan spiritual. Melalui komunitas seperti Lens Production Tari, kita diingatkan bahwa kebanggaan terhadap budaya tidak harus datang dari masa lalu, tapi bisa tumbuh dan menari bersama langkah kaki generasi hari ini.
Penulis
Pratika Martha Lena
Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Pasca Sarjana Jakarta