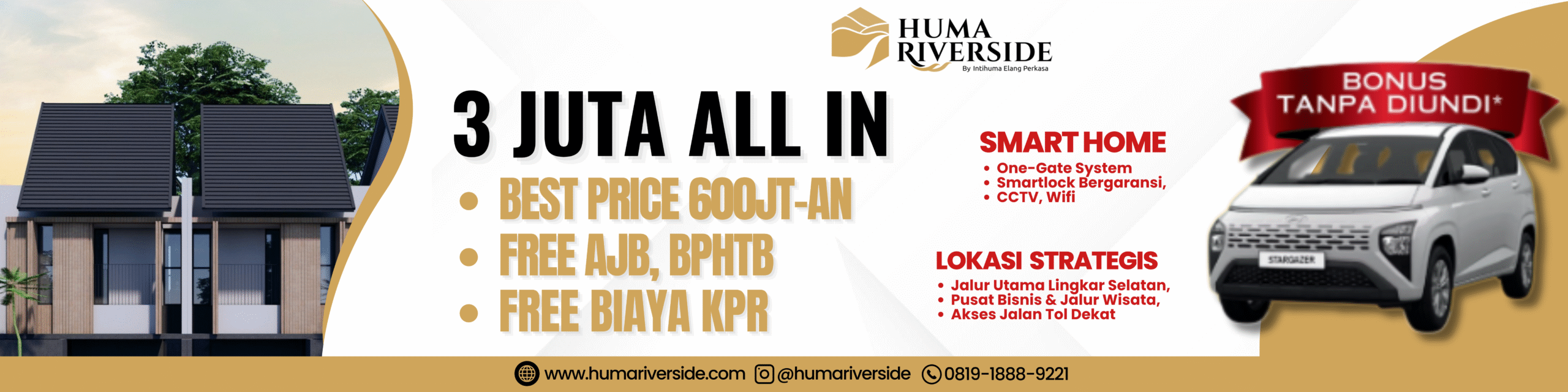Ketika Cinta Bertemu Perbedaan: Tantangan dan Adaptasi Komunikasi Budaya dalam Keluarga Batak-Jawa
Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan, khususnya ketika terjadi percampuran budaya dalam institusi sekecil rumah tangga (Koentjaraningrat, 2009).
Salah satu contoh konkret adalah pernikahan antara individu dari suku Batak (Sumatera Utara) dan suku Jawa (Jawa Timur), yang memiliki perbedaan signifikan dalam gaya komunikasi, nilai-nilai budaya, hingga penggunaan bahasa sehari-hari. Ketika dua latar belakang ini bersatu dalam sebuah ikatan keluarga, tidak jarang muncul ketegangan yang dipicu oleh perbedaan pola pikir dan ekspresi emosional (Ting-Toomey, 1999).
Suami dari suku Batak, misalnya, sering kali dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas, terus terang, dan ekspresif. Sebaliknya, istri dari suku Jawa, terutama dari Malang, lebih cenderung menjunjung tinggi sopan santun, keharmonisan, dan menghindari konflik terbuka. Ketimpangan komunikasi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berulang jika tidak dikelola dengan baik.
Fenomena culture shock menjadi hal yang wajar dalam dinamika rumah tangga lintas budaya. Ketika pasangan dihadapkan pada kebiasaan yang sangat berbeda dari yang mereka kenal sejak kecil, rasa kaget, bingung, bahkan stres dapat terjadi. Inilah yang sering menjadi akar dari pertengkaran dalam rumah tangga multikultural (Gudykunst, 2003).
Perbedaan bukan hanya terjadi pada gaya komunikasi verbal, tetapi juga pada bahasa tubuh, cara menyampaikan pendapat, dan ekspektasi terhadap peran gender. Dalam budaya Batak, misalnya, kepala keluarga cenderung mengambil peran dominan, sementara dalam budaya Jawa, pendekatan yang lebih egaliter kadang dianggap lebih ideal. Bentuk-bentuk penyesuaian ini juga mencakup aspek spiritual dan adat istiadat. Ritual-ritual tertentu dari salah satu pihak bisa dianggap aneh atau tidak perlu oleh pihak lainnya.
Ketegangan akan meningkat bila tidak ada dialog dan saling pengertian yang terus-menerus dilakukan. Dengan demikian, pernikahan lintas budaya tidak bisa hanya mengandalkan cinta dan komitmen emosional semata. Diperlukan kesadaran budaya, empati, dan kesediaan untuk saling belajar agar komunikasi dalam keluarga tetap sehat dan produktif (Rachmat, 2007).
Pertemuan dua budaya dalam rumah tangga sering kali menimbulkan gesekan. Pada awal pernikahan, pasangan dari dua budaya ini kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Pertengkaran kecil dapat membesar hanya karena perbedaan cara menyampaikan emosi atau ekspektasi terhadap peran masing-masing dalam keluarga (Tempo.co, 2022).
Misalnya, ketika suami berbicara dengan nada tinggi sebagai bentuk ekspresi biasa dalam budaya Batak, istri bisa merasa terintimidasi atau tidak dihargai. Sebaliknya, ketika istri terlalu hati-hati dan pasif dalam menyampaikan kritik, suami bisa menilainya sebagai tidak terbuka atau menyimpan ketidaksenangan.
Masalah ini bukan sekadar soal perbedaan karakter, tetapi lebih dalam lagi menyangkut nilai-nilai budaya yang tertanam sejak kecil. Pola asuh, kebiasaan makan, etika berbicara, hingga tata cara menyambut tamu, semuanya bisa menjadi sumber konflik yang tidak disadari.
Jika tidak ada kesepahaman sejak awal, konflik ini bisa berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menyadari bahwa mereka tidak hanya menikah dengan individu, tetapi juga dengan budayanya.
Menghadapi perbedaan budaya dalam rumah tangga memerlukan strategi komunikasi yang matang. Salah satu pendekatan yang relevan adalah integrative adaptation, di mana masing-masing pasangan berusaha mempertahankan identitas budayanya sambil membuka ruang untuk menerima budaya pasangannya (Gudykunst, 2003).
Strategi ini menekankan pentingnya saling mendengarkan dan menciptakan dialog yang aman untuk mengungkapkan perbedaan tanpa menghakimi. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan maksud, tetapi juga jembatan untuk membangun rasa saling menghormati.
Dalam konteks keluarga Batak-Jawa, proses adaptasi juga berarti membuka diri terhadap tradisi keluarga pasangan. Misalnya, pasangan bisa saling memperkenalkan kebiasaan budaya masing-masing melalui kegiatan harian, masakan, atau perayaan hari besar.
Adaptasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan kesabaran. Tidak ada cara instan untuk menyatukan dua nilai budaya yang sudah tertanam sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, penting untuk tidak menyerah ketika konflik muncul, tetapi menjadikannya sebagai proses pembelajaran.
Selain komunikasi interpersonal, peran pihak ketiga seperti mediator keluarga atau konselor pernikahan juga bisa sangat membantu. Dengan pendekatan yang netral dan profesional, mereka dapat membantu mengurai akar konflik dan memberikan saran praktis dalam mengelola perbedaan budaya (Moleong, 2002).
Pasangan perlu menciptakan budaya keluarga baru yang merupakan perpaduan dari dua budaya. Ini dapat menciptakan identitas keluarga yang unik, yang justru memperkuat keharmonisan dan solidaritas antar anggota keluarga. Pernikahan lintas budaya mencerminkan wajah asli masyarakat Indonesia yang plural.
Meski penuh tantangan, integrasi budaya melalui rumah tangga adalah langkah konkret dalam menciptakan masyarakat yang inklusif.
Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam membentuk kesadaran budaya generasi berikutnya. Anak-anak yang lahir dari pasangan multikultural akan memiliki pemahaman yang lebih luas, toleran, dan fleksibel terhadap perbedaan.
Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada bagaimana orang tua mengelola perbedaan tersebut. Jika konflik disembunyikan dan tidak diatasi dengan cara terbuka, anak justru akan mengalami kebingungan identitas dan kecenderungan menolak salah satu budaya.
Refleksi ini juga menunjukkan pentingnya literasi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sering kali, pasangan menikah tanpa pemahaman mendalam tentang budaya pasangannya, yang kemudian menjadi sumber konflik jangka panjang (Ting-Toomey, 1999).
Seni, media, dan pendidikan dapat memainkan peran besar dalam mengedukasi masyarakat tentang tantangan pernikahan lintas budaya. Program pranikah atau pelatihan komunikasi antarbudaya bisa menjadi bagian dari kebijakan sosial yang progresif.
Penting juga untuk memperkuat nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati dalam konteks multikultural. Nilai-nilai ini bisa menjadi fondasi etis dalam membangun keluarga yang harmonis meski berasal dari budaya berbeda.
Kita juga perlu mendorong narasi yang lebih positif tentang pernikahan lintas budaya. Alih-alih dianggap sebagai masalah, ia seharusnya dilihat sebagai peluang untuk memperkaya pengalaman hidup dan memperkuat jalinan sosial.
Dengan cara itu, komunikasi budaya tidak hanya menjadi alat untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan menyatukan perbedaan demi tujuan bersama: keluarga yang kuat dan masyarakat yang rukun.
Perbedaan budaya dalam rumah tangga bukanlah penghalang untuk menciptakan kebahagiaan. Justru, dengan komunikasi yang tepat, perbedaan bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas dalam membangun kehidupan bersama.
Pasangan dari budaya Batak dan Jawa menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang usaha memahami dan menerima satu sama lain secara utuh.
Proses ini tidak selalu mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Ketika perbedaan dirangkul dan dikelola dengan bijak, keluarga menjadi tempat paling indah untuk belajar toleransi, kesetaraan, dan cinta yang tidak bersyarat.
Penulis
Pratika Martha Lena
Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Pasca Sarjana Jakarta