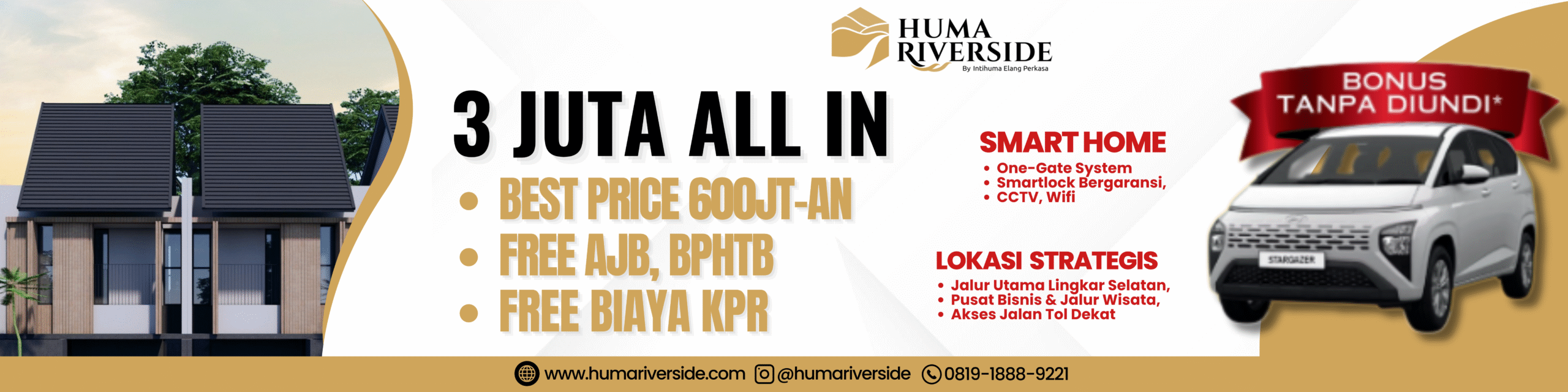Melebur Lewat Rasa: Adaptasi Budaya Masyarakat Indonesia Terhadap Gelombang Makanan Korea
Globalisasi telah membuka ruang interaksi budaya lintas negara yang semakin intens. Salah satu wujudnya yang sangat terasa di Indonesia adalah gelombang Hallyu atau Korean Wave yang tidak hanya hadir melalui musik dan drama Korea, tetapi juga lewat sektor kuliner.
Maraknya makanan Korea di Indonesia menjadi bukti konkret dari dinamika komunikasi antar budaya yang terjadi melalui medium rasa dan makanan. Dari restoran waralaba Korea hingga jajanan pinggir jalan bertema K-Food, masyarakat Indonesia kini semakin akrab dengan makanan seperti kimchi, tteokbokki, ramyeon, hingga bulgogi.
Konsumen Indonesia yang sangat terbuka akan tren dan pengalaman baru adalah Gen Z dan Millenial. Mereka merupakan penggemar K-Pop dan K-Drama. Menurut Survey Yougove pada 2024, lebih dari 60 persen Gen Z di Indonesia tertarik untuk mencoba makanan Korea. Selain itu Indonesia juga merupakan salah satu pasar Ramen terbesar di dunia dengan konsumsi lebih dari 14 milyar porsi per tahun (World Instant Noodles Association-2024).
Dalam perspektif komunikasi antar budaya, makanan tidak hanya berperan sebagai kebutuhan fisiologis, melainkan juga sebagai simbol budaya yang sarat makna. Makanan menjadi bentuk ekspresi budaya yang konkret, membawa serta nilai-nilai, norma, bahkan identitas suatu kelompok masyarakat.
Samovar, Porter, dan McDaniel (2010) menekankan bahwa budaya sangat memengaruhi tidak hanya apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana makanan dikonsumsi, kapan, dan dalam konteks sosial seperti apa aktivitas makan itu dilakukan. Maka dari itu, makanan adalah saluran komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan budaya secara implisit namun kuat.
Adaptasi budaya menjadi kunci utama dalam menjembatani selera lokal dengan cita rasa asing. Banyak pelaku bisnis kuliner Korea di Indonesia melakukan adaptasi dengan cara menyajikan makanan Korea yang telah dimodifikasi sesuai preferensi masyarakat Indonesia baik dari segi rasa, tingkat kepedasan, harga, hingga penyajian halal. Contohnya adalah kehadiran tteokbokki dengan sambal khas Indonesia, atau ramyeon instan berlabel halal yang kini dijual luas di minimarket.
Media sosial menjadi saluran utama dalam menyebarkan citra dan daya tarik makanan Korea
Influencer, food vlogger, hingga komunitas pecinta Korea berperan aktif dalam memperkenalkan makanan Korea melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Representasi makanan Korea yang ditampilkan dalam drama dan variety show Korea juga turut membentuk persepsi positif terhadap K-Food di mata konsumen Indonesia.
Visualisasi yang menarik, narasi kebersamaan saat makan (seperti budaya “mukbang”), serta romantisasi aktivitas makan dalam budaya Korea menjadikan makanan Korea sebagai bagian dari gaya hidup modern. Komunikasi visual dan simbolik ini memperkuat minat masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, terhadap budaya Korea secara keseluruhan.
Meskipun fenomena masuknya makanan Korea (K-Food) ke Indonesia menunjukkan penerimaan yang luas di berbagai kalangan masyarakat terutama generasi muda, hal tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga menghadirkan tantangan dan isu budaya yang kompleks. Dalam ranah komunikasi antar budaya, setiap bentuk kontak budaya tidak hanya menawarkan peluang untuk saling mengenal, tetapi juga menyimpan potensi gesekan nilai dan identitas.
Di satu sisi, gelombang K-Food membuka ruang bagi toleransi budaya dan penghargaan terhadap keberagaman. Interaksi dengan budaya asing melalui makanan memungkinkan individu memperluas cakrawala budaya mereka, memahami nilai-nilai dari bangsa lain, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat global. Makanan menjadi titik temu yang bersifat netral dan menyenangkan untuk saling mengenal dan memahami perbedaan.
Makanan adalah identitas
Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran akan dominasi budaya asing, terutama ketika tren makanan Korea dianggap terlalu dominan dan menggeser budaya lokal. Fenomena ini dikenal sebagai bentuk cultural homogenization, di mana budaya lokal lambat laun kehilangan ruang ekspresi karena terpinggirkan oleh budaya global yang lebih agresif dan terindustrialisasi.
Contohnya, semakin banyak restoran yang menyajikan makanan Korea di pusat perbelanjaan, sementara kuliner tradisional Indonesia justru terpinggirkan atau tidak mengalami modernisasi yang setara dari sisi branding dan kemasan.
Dalam hal ini, komunikasi antar budaya tidak boleh hanya berjalan satu arah. Keterbukaan terhadap budaya asing seperti Korea harus dibarengi dengan upaya mempertahankan identitas budaya lokal, khususnya dalam hal kuliner. Dibutuhkan kebijakan budaya yang mendorong penguatan kuliner lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang tetap relevan di tengah arus globalisasi.
Tantangan budaya bukan berarti penghalang, melainkan kesempatan untuk menciptakan dialog antar budaya yang konstruktif, di mana budaya lokal dan global bisa saling memperkaya, bukan saling meniadakan. Penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan komunitas kuliner, untuk bersama-sama membangun ekosistem komunikasi lintas budaya yang inklusif dan berkeadilan, menjaga identitas lokal sambil tetap membuka diri terhadap pengaruh luar secara kritis dan selektif.
Jika Indonesia ingin mempertahankan identitas budayanya, maka kuliner lokal harus dihidupkan kembali melalui strategi komunikasi budaya yang kreatif dan terstruktur. Bukan hanya soal rasa, tapi juga citra, cerita, dan keberpihakan kebijakan. Dalam era global, makanan Indonesia tak boleh sekadar jadi warisan, harus jadi masa depan.
Uci Hasmana
Mahasiswa Pascasarjana
Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta