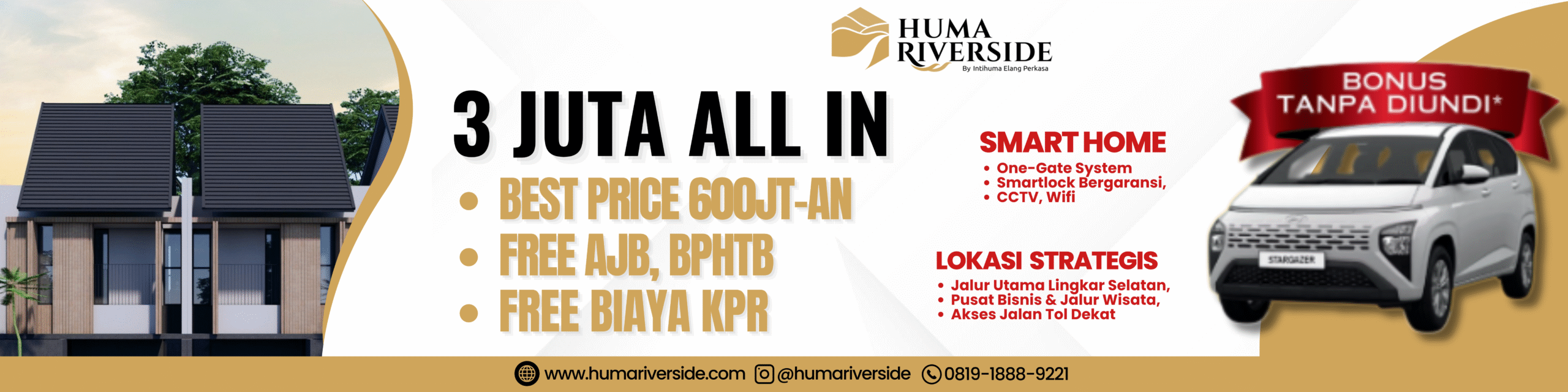Membuka Ruang Bicara tentang Vasektomi
Program Keluarga Berencana (KB) diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1957 dengan fokus pembangunan untuk mewujudkan keluarga sejahtera melalui tiga macam pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.
Penerimaan masyarakat terhadap program KB juga sangat bervariasi, ada yang mau dengan suka rela menggunakan alat kontrasepsi dan ada juga yang tidak. Pada saat itu pemahaman masyarakat terhadap nilai “ banyak anak banyak rejeki” sangatlah kuat.
Menjalankan Program KB dengan menggunakan Modern Kontrasepsi, terutama bagi pria yaitu vasektomi bukanlah perkara mudah. Bermacam pendekatan dilakukan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta hasil kerja keras para kader di desa.
Pendekatan ini diraskaan sangat efektif sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan dengan sangat signifikan. Angka kelahiran total (TFR) pada saat itu berjumlah 5,6 yang berarti seorang perempuan melahirkan sekitar 5-6 anak selama masa reproduksinya, namun pada saat ini menjadi 2,1 dimana perempuan hanya melahirkan 2-3 anak saja. Hal ini menunjukan keberhasilan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Pada saat ini, ditengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan terkait keluarga berencana, vasektomi masih menjadi topik yang tabu di banyak masyarakat. Meskipun metode kontrasepsi permanen ini telah terbukti aman dan efektif, persepsi negatif terhadap vasektomi terus hidup, diperkuat oleh nilai-nilai budaya, norma gender, dan mitos sosial.
Hal ini terbukti dengan tingkat capaian program KB dengan metode kontrasepsi vasektomi paling rendah dibandingkan dengan metode kotrasepsi lainnya yaitu 0,13% ditahun 2024 (Data Pengendalian Lapangan KB – BKKBN 2024)
Bagaimana membuka ruang bicara tentang vasektomi di tengah kuatnya stigma budaya? Di sinilah pentingnya komunikasi antar budaya, sebuah pendekatan yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengupayakan dialog yang inklusif dan sensitif terhadap latar belakang nilai-nilai masyarakat. Artikel ini mengulas bagaimana komunikasi antar budaya dapat menjadi sarana transformasi persepsi, yang tidak hanya mengikis prasangka, tetapi juga membangun pemahaman baru yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat.
Vasektomi kerap dibayangkan secara keliru sebagai tindakan yang menghilangkan kejantanan, menurunkan fungsi seksual, atau bahkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kodrat laki-laki sebagai “pemberi keturunan.” Dalam budaya yang masih menjunjung tinggi peran dominan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, kemampuan reproduksi pria sering kali dianggap sebagai simbol kehormatan, kekuasaan, dan harga diri.
Oleh karena itu, keputusan laki-laki untuk secara sukarela melakukan vasektomi kerap dipandang menyimpang dari norma, tidak wajar, bahkan memalukan. Stigma ini tidak muncul begitu saja; ia dibentuk dan diperkuat oleh rendahnya literasi kesehatan reproduksi, penyebaran informasi yang keliru, serta narasi-narasi negatif yang diwariskan secara turun-temurun melalui pola komunikasi dalam lingkungan sosial.
Dalam konteks inilah, komunikasi antar budaya memegang peran penting. Sebagai proses interaksi yang menghargai keberagaman nilai, keyakinan, dan norma lokal, komunikasi ini memungkinkan penyampaian pesan kesehatan berlangsung secara inklusif dan empatik.
Dalam promosi program vasektomi, pendekatan ini tidak hanya mampu menghindari resistensi akibat ketidaksesuaian norma, tetapi juga membuka ruang dialog yang setara dan membangun. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya, informasi tentang vasektomi dapat diterima sebagai bagian dari pilihan rasional yang selaras dengan nilai-nilai.
Menurut teori Anxiety/Uncertainty Management dari Gudykunst (2005), komunikasi yang efektif dalam konteks antar budaya harus mampu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian melalui empati, kesabaran, dan kejelasan pesan. Artinya, pembicaraan tentang vasektomi harus dimulai bukan dari ajakan melakukan, tetapi dari dialog yang mendengarkan kekhawatiran dan nilai-nilai masyarakat terlebih dahulu.
Salah satu bentuk konkret komunikasi antar budaya adalah dialog budaya, ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan nilai-nilai lokal bertemu dengan pengetahuan medis modern secara sejajar, bukan saling menegasikan.
Contoh-contoh yang dapat dilakukan untuk membuka ruang komunikasi terhadap vasektomi diantaranya melalui Forum komunitas yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tenaga kesehatan untuk membahas kesehatan reproduksi secara terbuka.
Testimoni dari laki-laki yang sudah menjalani vasektomi dan masih diterima di komunitasnya, digunakan sebagai narasi pembuka. Serta Pertunjukan budaya atau cerita rakyat yang dimodifikasi untuk menyisipkan tema kesetaraan dalam keluarga dan tanggung jawab bersama dalam keluarga berencana.
Pendekatan ini terbukti jauh lebih efektif dibanding kampanye satu arah dari luar yang sering ditolak karena dianggap tidak menghargai kearifan lokal.
Dalam sebuah studi lapangan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah organisasi kesehatan bekerja sama dengan pemimpin adat untuk membuka diskusi seputar peran laki-laki dalam keluarga berencana. Awalnya, topik vasektomi ditolak secara keras. Namun setelah melalui dialog-dialog budaya yang melibatkan simbol dan narasi lokal, terjadi perubahan signifikan.
Seorang kepala suku berkata:”Kalau laki-laki bisa jadi pelindung keluarga, dia juga harus bisa jadi pelindung masa depan anak-anaknya, termasuk dengan menjaga agar keluarganya tidak terbebani.”
Pernyataan ini menjadi titik balik yang memperlihatkan bahwa budaya tidak selalu menjadi penghalang, tetapi bisa menjadi alat untuk merumuskan ulang makna kesehatan reproduksi.
Agar komunikasi tentang vasektomi bisa diterima, perlu strategi yang mempertimbangkan unsur budaya sebagai kekuatan, bukan ancaman. Perlu mengenali sistem nilai masyarakat, memetakan kepercayaan, peran gender, simbol, dan bahasa lokal sebagai bagian dari strategi penyampaian pesan.
Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah membangun koalisi dengan tokoh-tokoh lokal, baik dari kalangan adat maupun agama, yang memiliki otoritas sosial untuk memengaruhi opini publik. Peran mereka sangat signifikan dalam mengubah narasi dan membuka ruang penerimaan terhadap isu-isu sensitif seperti vasektomi.
Selain itu, penyediaan ruang dialog yang aman, inklusif, dan bebas penghakiman menjadi kunci dalam membangun kepercayaan. Masyarakat perlu merasa dihargai ketika mereka bertanya, menyampaikan ketakutan, atau meragukan informasi yang diberikan.
Mendukung ruang bicara yang aman tidak menghakimi, memberi tempat untuk bertanya, berdialog, dan mengungkap ketakutan secara terbuka. Menyesuaikan format dan bahasa komunikasi gunakan pendekatan visual, cerita, metafora lokal, dan bahasa ibu.
Untuk itu sangat perlu untuk menampilkan identitas laki-laki yang bertanggung jawab
bukan dengan mendekonstruksi maskulinitas secara frontal, tetapi dengan membentuk narasi baru tentang maskulinitas yang peduli, bertanggung jawab, dan rasional.
Vasektomi tidak akan bisa diterima hanya dengan pendekatan medis dan data statistik. Diperlukan pendekatan budaya yang humanistik dan komunikatif. Melalui komunikasi antar budaya, masyarakat dapat didorong untuk membuka ruang dialog, Komunikasi antar budaya memungkinkan terjadinya proses refleksi sosial, di mana masyarakat diajak untuk mengkritisi stigma yang telah lama membentuk cara pandang mereka, sekaligus membuka ruang bagi terbentuknya pemahaman baru yang lebih adil secara gender.
Melawan stigma bukan berarti menyerang budaya yang ada, tetapi justru membangun dialog di dalamnya. Dalam dialog itulah, vasektomi dapat dimaknai sebagai wujud tanggung jawab laki-laki terhadap kesehatan keluarga, tanpa kehilangan identitas mereka sebagai pria.
Uci Hasmana
Mahasiswa Pascasarjana
Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta