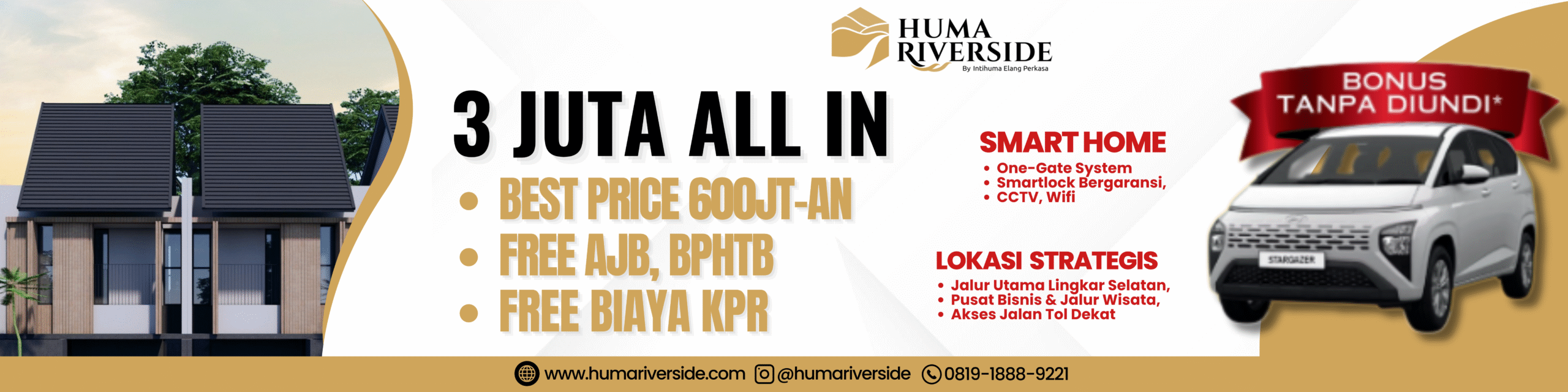Tarian Gonjet sebagai Simbol Kritik Sosial: Kesenjangan dan Keadilan di Negeri Sendiri
Kesenjangan sosial di Indonesia telah menjadi persoalan klasik yang hingga kini masih membelit kehidupan masyarakat. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan berbagai wajah dan bentuk.
Ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan terutama dalam sistem hukum menjadi wajah paling mencolok dari kesenjangan sosial yang ada. Masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, menyaksikan realitas ini dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu bentuk paling nyata dari kesenjangan ini adalah ketimpangan perlakuan hukum antara kalangan borjuis atau elite dan masyarakat biasa. Ungkapan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” sudah sangat populer sebagai cerminan ironi penegakan hukum yang tidak adil (Tempo.co, 2023).
Kasus-kasus hukum yang melibatkan rakyat kecil seringkali diselesaikan dengan proses yang panjang dan hukuman berat, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang berkuasa kerap kali berakhir dengan vonis ringan atau bahkan impunitas.
Dalam konteks ketimpangan ini, seni dan budaya memiliki kekuatan untuk menjadi media kritik sosial yang efektif dan menyentuh. Melalui pendekatan yang bersifat estetis namun menyimpan makna mendalam, seni dapat menyuarakan kegelisahan masyarakat dan memberikan kesadaran kolektif tentang perlunya perubahan. Salah satu bentuk seni yang memiliki kekuatan tersebut adalah seni tari.
Karya tari yang mengambil dasar dari tari cokek Betawi ini merupakan bentuk ekspresi artistik yang kuat dalam menyampaikan realitas sosial.
Tari cokek sendiri dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat Betawi yang sarat dengan gerakan khas dan ekspresi dinamis. Dalam karya ini, elemen-elemen seperti selut, selancar, kewer, dan silat dikembangkan untuk menggambarkan simbol-simbol ketimpangan sosial dan ketidakadilan hukum.
Gerakan selut dan selancar mencerminkan usaha masyarakat kecil untuk terus bergerak dan bertahan di tengah tekanan hidup yang tak berkesudahan.
Kewer melambangkan ketegangan dan kegelisahan sosial, sementara silat menjadi simbol dari perlawanan atau upaya membela diri dari sistem yang tidak adil. Gerakan-gerakan ini dirangkai dalam narasi visual yang menyentuh dan mengajak penonton untuk merefleksikan kondisi sosial di sekitar mereka.
Pendekatan komunikasi yang digunakan dalam tarian ini menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai pihak yang terpinggirkan.
Dalam setiap babak tarian, terlihat bagaimana mereka diperlakukan tidak adil, disingkirkan, dan bahkan dilecehkan oleh sistem. Sementara itu, kelompok elite digambarkan sebagai pihak yang selalu berada di posisi aman dan dominan, menikmati kekuasaan tanpa mempertanggungjawabkannya.
Melalui visualisasi gerakan dan ekspresi tubuh, tarian ini berbicara tanpa kata. Ia menyuarakan bahwa keadilan di negeri ini belum sepenuhnya berpihak kepada semua.
Dalam tarian ini, masyarakat diajak untuk bertanya: Apakah keadilan memang harus memandang kasta? Sebuah pertanyaan retoris yang menantang kita semua untuk melihat lebih dalam tentang nilai-nilai keadilan yang seharusnya tidak memihak.
Tari cokek sebagai basis gerakan dalam karya ini memiliki akar budaya yang erat dengan masyarakat Betawi. Keunikan geraknya yang lincah dan ekspresif menjadi medium yang kuat untuk menyampaikan pesan simbolik. Dalam tarian ini, setiap gerakan ditata sedemikian rupa untuk menggambarkan dinamika sosial—konflik, tekanan, resistensi, dan harapan (Yuliani, 2019).
Ragam gerakan tersebut menyampaikan narasi tentang pertarungan batin dan fisik masyarakat kelas bawah dalam menghadapi realitas sosial yang timpang.
Selut dan selancar, sebagai gerakan utama dalam tari ini, menggambarkan kelincahan rakyat kecil dalam bertahan hidup meski terus tertekan oleh sistem. Mereka terus bergerak, mencari celah untuk bertahan dan hidup layak di tengah ketidakadilan.
Kewer melambangkan ketegangan sosial yang tak kunjung reda, suatu simbolisasi dari konflik horizontal maupun vertikal yang tak terhindarkan. Sementara itu, gerakan silat menjadi metafora dari upaya pembelaan diri, perjuangan untuk hak dan martabat, serta perlawanan simbolik terhadap dominasi sistem.
Tarian ini tidak hanya menjadi pertunjukan estetika, melainkan juga kritik terhadap fenomena ketidakadilan hukum yang begitu nyata. Dalam konteks hukum Indonesia, kita menyaksikan bagaimana kasus-kasus korupsi kelas kakap seringkali berakhir ringan, sementara pelanggaran kecil oleh rakyat biasa bisa berbuntut panjang.
Ketimpangan ini diperparah dengan masih kuatnya budaya patronase dan oligarki dalam sistem pemerintahan kita, menciptakan struktur sosial yang menindas secara sistemik (Kompas.com, 2022).
Pertanyaan mendasar yang ingin disampaikan lewat tarian ini adalah: Apakah keadilan harus memandang kasta? Apakah hukum harus memberi perlakuan berbeda berdasarkan status sosial? Sejatinya, prinsip hukum adalah equality before the law—kesetaraan di hadapan hukum (Soekanto, 2007).
Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut kerap kali hanya menjadi slogan kosong, dan tarian ini hadir untuk mengingatkan bahwa keadilan sejati semestinya tidak bersyarat.
Tarian ini mengajak kita untuk merenung, bahwa seni bukan hanya soal hiburan, tetapi juga tentang perlawanan, kesadaran, dan pembebasan. Dengan menggabungkan unsur tradisional seperti cokek dengan tema kontemporer tentang ketimpangan sosial, karya ini menyentuh lapisan emosional dan intelektual masyarakat. Seni tari, dalam konteks ini, menjadi instrumen yang mampu menyampaikan pesan-pesan sosial secara halus namun mengena (Koentjaraningrat, 2002).
Pesan dalam tarian ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada para pemangku kebijakan dan pemimpin negeri.
Kritik yang disampaikan melalui gerakan tari lebih mudah diterima karena menghindari konfrontasi langsung, namun tetap kuat dalam menggugah kesadaran. Ini menjadikan seni sebagai alat yang strategis dalam membangun dialog sosial dan menantang struktur ketidakadilan yang sudah mengakar.
Refleksi sosial dari karya ini memperlihatkan bahwa ketimpangan bukanlah takdir, melainkan hasil dari sistem yang bisa diubah. Masyarakat memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan tersebut melalui solidaritas dan keberanian menyuarakan kebenaran. Karya seni menjadi medium edukasi yang membuka ruang diskusi publik dan merangsang empati terhadap mereka yang selama ini dipinggirkan (Bourdieu, 1998).
Dengan demikian, tarian ini bukan sekadar dokumentasi budaya, melainkan juga bentuk perlawanan kultural terhadap ketimpangan sosial. Ia menjadi representasi dari harapan, perjuangan, dan peringatan bahwa keadilan harus terus diperjuangkan. Lewat tarian, kita diingatkan bahwa budaya bukan sekadar warisan, melainkan alat perjuangan yang hidup dan terus relevan dalam dinamika sosial saat ini.
Kesenjangan sosial dan ketimpangan hukum adalah masalah sistemik yang memerlukan solusi holistik. Melalui karya seni tari, isu ini dapat dijangkau dengan pendekatan yang lebih emosional dan komunikatif. Tarian yang berpijak pada tradisi lokal namun menyuarakan kegelisahan masa kini menjadi simbol bahwa budaya masih hidup dan relevan dalam perjuangan sosial.
Lebih dari sekadar tontonan, tarian ini hadir sebagai ruang kritik yang menyuarakan harapan masyarakat kecil akan keadilan yang sejati. Ia menggambarkan kenyataan pahit yang dialami oleh masyarakat kelas bawah, namun sekaligus menawarkan harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi melalui kesadaran kolektif dan solidaritas sosial.
Di tengah pesimisme terhadap sistem yang timpang, karya seni seperti ini hadir sebagai pengingat akan pentingnya suara dari akar rumput. Suara yang sering kali dibungkam, namun melalui seni, mampu menembus batas dan menyampaikan pesan ke semua kalangan, termasuk mereka yang berkuasa. Keadilan bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat.
Tarian ini mengajak kita untuk terus mempertanyakan, menggugat, dan memperjuangkan sistem yang lebih adil dan manusiawi. Sebab budaya bukan hanya cerminan masyarakat, tetapi juga alat perubahan sosial yang kuat dan bermakna.
Penulis
Pratika Martha Lena
Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Pasca Sarjana Jakarta